Pengenalan Betawi dari masa ke masa
Abad ke-2
Jakarta termasuk kekuasaan salakanagara,dan era perdagaangan maju ke Tiongkok
Wilayah yang kini dikenal sebagai Jakarta dan sekitarnya dihuni oleh penduduk yang merupakan leluhur suku Betawi. Daerah ini masuk dalam kekuasaan Kerajaan Salakanagara atau Holoan, yang berpusat di kaki Gunung Salak.
Masyarakat yang mendiami wilayah muara Sungai Ciliwung saat itu dikenal sebagai orang-orang pesisir yang akrab dengan perniagaan. Mereka menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain dari berbagai penjuru. Aktivitas perdagangan ini berkembang pesat, bahkan pada tahun 432 Masehi, Kerajaan Salakanagara sudah tercatat mengirim utusan dagang ke Cina. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa itu, wilayah Betawi telah menjadi pusat perniagaan yang strategis dan terbuka bagi interaksi dengan dunia luar.
Para ahli sejarah berpendapat bahwa pada masa ini, masyarakat Betawi sudah memiliki corak kebudayaan sendiri, yang dibuktikan dengan penemuan anting-anting di situs-situs arkeologis di daerah Babelan, Bekasi, Karawang, dan Subang. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan mereka telah berkembang jauh sebelum datangnya pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Melayu yang datang pada abad ke-10.

Abad ke-5
Berdirinya kerajaan Tarumanagara dan Sunda kelapa bagian dari kerajaannya
Pada akhir abad ke-5 Masehi, wilayah yang dihuni oleh leluhur suku Betawi mulai berada di bawah pengaruh Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Hindu ini berpusat di tepi Sungai Candrabagha (diidentifikasi sebagai Sungai Bekasi), yang menandai masuknya kekuasaan baru di Jawa bagian barat.
Berbeda dengan kerajaan sebelumnya yang berfokus pada perdagangan, Raja Tarumanagara cenderung berfokus pada sektor pertanian. Kerajaan ini aktif membangun banyak bendungan untuk mendukung sistem irigasi. Akibatnya, masyarakat setempat, termasuk orang-orang Betawi, mulai mengenal persawahan menetap untuk pertama kalinya.
Pada masa ini, wilayah Betawi, yang mencakup daerah pesisir seperti Sunda Kelapa, menjadi bagian dari kekuasaan Tarumanagara. Menurut sejarawan Ridwan Saidi, populasi penduduk Betawi saat itu sudah sangat besar, diperkirakan mencapai 100.000 jiwa. Jumlah penduduk yang signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Betawi telah membentuk identitas kebudayaan yang khas, bahkan sebelum datangnya pengaruh besar dari luar.

Abad ke-7
Pengaruh Sriwijaya dan Pergeseran Budaya
Pada abad ke-7, wilayah yang didiami oleh leluhur suku Betawi mengalami perubahan signifikan. Kerajaan Tarumanagara, yang sebelumnya berkuasa, ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang kuat dari Sumatra.
Mata Pencaharian: Penaklukan ini membawa perubahan ekonomi yang penting. Jika Tarumanagara berfokus pada pertanian, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim kembali menghidupkan sektor perdagangan. Masyarakat Betawi yang tinggal di pesisir, khususnya di sekitar muara Sungai Ciliwung, kembali aktif sebagai pedagang dan menjalin hubungan dengan berbagai bangsa.
Perubahan Bahasa: Pengaruh terbesar dari Sriwijaya adalah pergeseran budaya dalam hal bahasa. Bahasa asli masyarakat Betawi, yaitu bahasa Kawi atau Jawa Kuno, mulai tergeser oleh bahasa Melayu. Bahasa ini menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan yang digunakan dalam perdagangan. Penyebaran bahasa Melayu terjadi melalui perkawinan campur antara penduduk asli dan para pendatang. Awalnya, bahasa ini hanya dipakai di daerah pesisir, tetapi seiring waktu menyebar ke pedalaman, termasuk di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede.

Abad ke-10
Dominasi Kerajaan Buddha dan Integrasi Budaya
Pada abad ke-10, wilayah Batavia kuno (cikal bakal masyarakat Betawi) berada di bawah pengaruh kuat Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Sriwijaya berhasil mengukuhkan hegemoni politiknya di jalur perdagangan Nusantara, termasuk di kawasan pesisir utara Jawa bagian barat.Kejayaan Sriwijaya sebagai pusat maritim menyebabkan perdagangan di pesisir Ciliwung semakin berkembang. Masyarakat setempat tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga aktif menjadi pedagang, nelayan, dan pengrajin. Hubungan dagang dengan Tiongkok, India, serta kawasan Asia Tenggara lainnya memperkaya perekonomian dan membuka jalur interaksi budaya.Kekuatan Sriwijaya sebagai kerajaan Buddha membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Buddha dan simbol-simbol keagamaan mulai dikenal, tercermin dari peninggalan arsitektur, seni, dan sistem sosial. Selain itu, tradisi upacara keagamaan dan kebiasaan hidup gotong royong mendapat warna baru dari nilai-nilai Buddhis yang menekankan harmoni.Bahasa Melayu Kuno semakin mapan sebagai bahasa komunikasi utama, terutama dalam perdagangan antarbangsa. Walau masih ada penggunaan bahasa lokal, Melayu menjadi lingua franca yang mempercepat proses integrasi antara penduduk asli dengan para pendatang. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi fondasi bahasa Betawi di masa berikutnya.
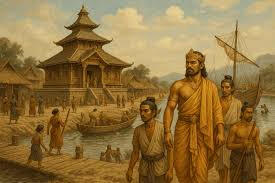
Abad ke-12
Pudarnya Dominasi Sriwijaya dan Bangkitnya Pajajaran
Memasuki abad ke-12, pengaruh Kerajaan Sriwijaya di bagian barat Jawa mulai menyusut akibat serangan dari luar serta melemahnya kontrol perdagangan. Di saat yang sama, Kerajaan Sunda–Pajajaran muncul sebagai kekuatan politik baru dengan pusat pemerintahannya di Batutulis, Bogor. Pergeseran ini membawa perubahan besar bagi masyarakat di pesisir utara Jawa, termasuk wilayah yang kelak menjadi tanah Betawi.Seiring melemahnya kendali Sriwijaya, jalur perdagangan di pesisir Ciliwung lebih banyak dikuasai oleh penguasa lokal yang berafiliasi dengan Pajajaran. Masyarakat pesisir kembali menyeimbangkan antara pertanian dan perdagangan. Produksi hasil bumi dari pedalaman—seperti beras, kayu, dan rempah—mengalir ke pelabuhan, lalu diperdagangkan dengan bangsa asing.Bangkitnya Pajajaran menandai kebangkitan budaya Sunda di wilayah barat Jawa. Tradisi keagamaan dan adat Sunda mulai memperkuat identitas masyarakat setempat. Nilai-nilai kekerabatan, tata upacara kerajaan, serta sistem hukum adat Sunda turut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di wilayah Batavia kuno.Bahasa Melayu tetap digunakan sebagai lingua franca perdagangan, tetapi di pedalaman dan lingkungan kerajaan, bahasa Sunda semakin mendominasi. Hal ini membuat masyarakat Betawi awal mengenal dua corak bahasa: Melayu di pesisir dan Sunda di pedalaman. Perpaduan ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan bahasa Betawi di masa mendatang.

Abad ke-14
Berdirinya Kerajaan Islam dan Menyebarnya Kedaulatan Baru
Pada abad ke-14, Islam mulai berakar kuat di pesisir utara Jawa dan melahirkan kekuatan politik baru, yaitu Kesultanan Demak. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus menggantikan dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Jawa. Pengaruhnya menjalar ke sekujur Nusantara, termasuk ke pelabuhan Sunda Kalapa yang kelak menjadi bagian penting dari sejarah Betawi.Dengan hadirnya Demak, aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pesisir makin meningkat. Masyarakat Betawi awal yang berada di sekitar muara Sungai Ciliwung semakin terlibat dalam jaringan dagang internasional, memperdagangkan beras, rempah, ikan, dan hasil bumi lain dengan pedagang Arab, Gujarat, hingga Tiongkok.Masuknya Islam membawa perubahan sosial dan budaya yang besar. Nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan, persaudaraan, dan solidaritas perlahan menggantikan praktik keagamaan lama. Tradisi baru muncul dalam bentuk upacara keagamaan Islam, seni musik bernuansa islami (seperti rebana), serta sistem pendidikan berbasis pesantren yang mulai dikenal masyarakat setempat.Bahasa Melayu semakin kuat posisinya sebagai bahasa penghubung. Penyebaran Islam memperkuat peran Melayu, karena bahasa ini digunakan para ulama dan pedagang dalam dakwah serta perjanjian dagang. Dari sinilah bahasa Betawi memperoleh banyak kosakata Arab dan Islam, yang melebur dengan unsur lokal dan membentuk identitas baru.
